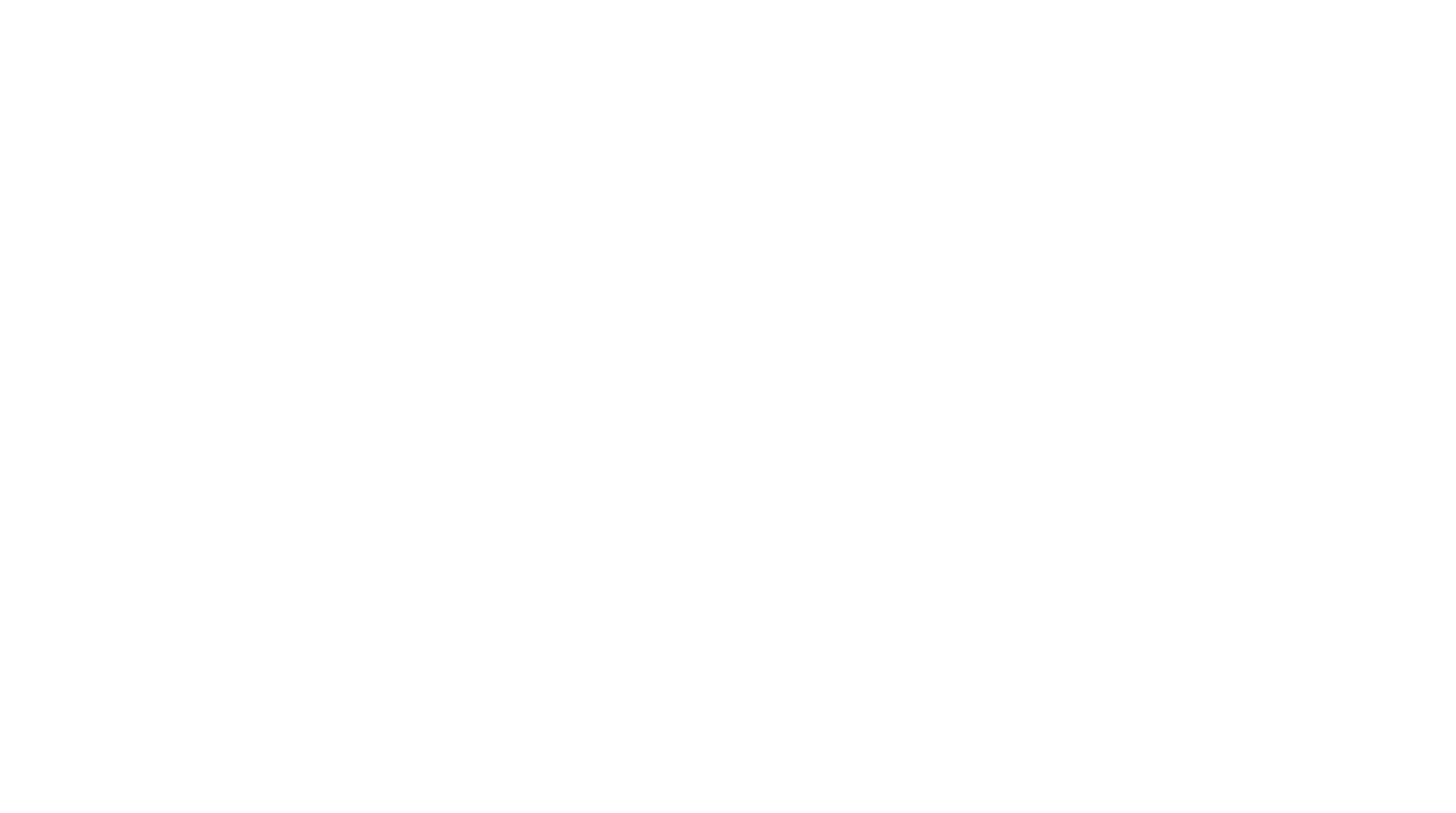Bagaimana perjalanan dr. Shela di CIMSA, dari CIMSA UI ke CIMSA Nasional?
Saya waktu itu masuk pada tahun 2010—saat saya mahasiswa tingkat II—dan ikut National Leadership Summit (national meeting CIMSA di awal tahun—red). Saya baru benar-benar ikut dan aktif terjun di tingkat III. Pada awal aktif di CIMSA UI, saya bertanggung jawab memegang majalah CIMSA UI sebagai Media and Communication Director CIMSA UI. Selain itu, saya sering ikut national meeting lainnya dan bertemu banyak teman. Saya merasa happy dan cukup aktif di nasional.
Di nasional, saya lebih tertarik kepada marketing, campaign, dan advocacy dan memutuskan untuk menjabat sebagai Marketing, Campaign, and Advocacy Director CIMSA. CIMSA adalah hal yang pertama kali memperkenalkan saya dengan advokasi. Selain level CIMSA yang grass root (secara horizontal ke masyarakat—red), CIMSA juga memiliki high level seperti advokasi. Advokasi tersebut ditujukan kepada policy maker di nasional. Saat menjabat sebagai MCAD CIMSA, saya banyak terpapar oleh advokasi.
Lain halnya dengan mindset orang Indonesia yang berpikir bahwa dokter adalah klinisi, saya menyadari bahwa bagi mahasiswa kedokteran di negara lain dokter dapat berkarir sebagai public health, campaign, advocacy, dan lainnya. Di saat tersebut saya cukup belajar advokasi dari America Society dan menjadi delegasi meeting PBB di New York. Pada meeting tersebut, saya semakin terpapar oleh banyak isu, terutama isu-isu noncommunicable diseases (NCDs)—dan saya menyukai isu tersebut. Saya juga belajar mengenai tobacco control dan memahami bahwa negara-negara lain memiliki kontrol tembakau yang sangat baik. Dulu, membicarakan tentang kontrol tembakau di Indonesia merupakan hal yang sangat susah. Ketika pulang dari Indonesia, saya membuat aliansi dengan fakultas-fakultas lain seperti Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Farmasi bertajuk ‘Gerakan Pemuda Anti Tembakau’. Hal tersebut mengantarkan saya untuk advokasi ke DPR, dan saya lanjutkan isu tersebut ke penerus saya di CIMSA (MCAD selanjutnya-red). Dari pengalaman tersebut, saya mendapatkan banyak sekali skill advokasi, networking, dan bonus pengalaman yang tidak terbayang sebelumnya.
Bagaimana kiprah dr. Shela di IFMSA?
Selanjutnya, saya turut mengikuti IFMSA di Asia Pasifik. Pertama, saya meng-apply posisi sebagai Regional Assistant Advocacy, Education, and Policy. Kita membuat central project mengenai tobacco control di IFMSA Asia Pasifik dan membuat panduan guideline untuk diteruskan dan dilaksanakan di NMO (National Medical Students Organization—red) masing-masing. Namun susahnya, vibe-nya terlalu loose, tidak mengikat sama sekali. Di IFMSA Asia Pasifik, tantangan yang saya rasakan adalah rasanya lebih tidak ada wewenang dan otoritas, bertugas hanya untuk membantu yang pusat, dan tidak memiliki garis koordinasi langsung yang jelas—sehingga outcome yang dihasilkan di NMO masing-masing tidak diketahui. Tahun berikutnya, saya kembali lanjut di IFMSA Asia Pasifik sebagai Regional Assistant SCOPH, turut mengontrol project dan membuat laporan. Ini semua saya kerjakan saat koas. Awalnya saya pikir bahwa setelah lulus preklinik, sudah tidak ada CIMSA dan IFMSA—tetapi ternyata saya salah.
Bagaimana dr. Shela sampai bisa menulis buku di penerbit luar negeri?
Karena ada network yang terjalin, saya jadi mengenal orang-orang IFMSA secara luas yang turut aktif. Kita memiliki project bersama dari IFMSA UK project yang masif, berjudul project textbook IFMSA. Textbook yang terlahir dari project tersebut adalah Essentials of Global Health—buku yang dibuat oleh mahasiswa kedokteran untuk mahasiswa kedokteran lainnya yang tertarik oleh isu-isu kesehatan masyarakat yang dibahas di dalamnya. Karena orang-orang di IFMSA mengetahui bahwa saya tertarik soal NCD, saya diajak menulis mengenai NCD—dan saya menulis chapter mengenai NCD. Hal ini membuat saya belajar lagi dan sadar bahwa networking yang saya miliki memiliki efek yang longlasting.
Bagaimana cara dr. Shela menyeimbangkan akademik dan pencapaian di CIMSA?
Kunci dari semua hal, bagi saya, baik saat mahasiswa, koas, maupun PPDS adalah atur waktu. Waktu adalah uang sehingga kamu harus treat waktu selayaknya uang. Ada tiga caranya, yaitu spend, invest, dan waste. Apabila kamu memilih invest, waktu tersebut akan berguna di masa depan. Hal yang saya pelajari adalah kita harus disiplin dengan diri sendiri—baik jadwal maupun tujuan kita. Cara pandang kita juga harus diubah bahwa time itu invest. Sebagai mahasiswa FK, tidak mungkin belajar 24 jam. Pasti ada waktu sehabis belajar yang dapat dipakai untuk melakukan hal lain. Bagi saya, saya banyak menulis di majalah, AORTA, maupun di Asia Pasifik (IFMSA MSI—red). Kerjakan saja apa yang kamu sukai asal ada manfaatnya. Jadi, saat kamu lihat kemarin (masa lalu—red), kamu tidak akan menyesal karena sudah invest pada sesuatu yang bermanfaat. Coba pikirkan lagi waktu yang telah dilalui saat suka dan bermanfaat. Menurut saya pasti bisa kok, kalau kalian mau.
Akan tetapi, tipikal anak FKUI kan rajin banget—takut terlewat sekolahnya, takut tertinggal ujiannya. Mungkin ada yang akan merasa sayang karena tidak bisa lulus tepat waktu. Namun, ada trade off yang saya lakukan—hal lain yang saya bisa dapatkan meskipun tidak lulus tepat waktu: pengalaman, menemui berbagai orang, dan mengerjakan banyak hal yang tidak pernah saya bayangkan. Hal tersebut tentu tidak apa-apa, itu kembali lagi pada pertimbangan dan pilihan diri sendiri.
Dok, cerita tentang menjadi delegasi CIMSA di sidang PBB, dong!
Sebagai delegasi CIMSA di General Assembly of UN (sidang umum tahunan PBB—red), mereka selalu memiliki isu khusus. Pada tahun 2012, salah satu isu yang dibawa adalah noncommunicable disease (NCD). Karena waktu itu saya belajar advokasi dari American Cancer Society, saya turut terlibat di sidang tersebut sebagai Global Cancer Ambassador. Sidang tersebut adalah sesuatu yang besar. Namun, ternyata dalam sidang tersebut semua orang sudah membawa hasil masing-masing yang hanya tinggal diketok (disahkan dalam sidang—red). Sebelum ada hasilnya, aku turut terlibat dalam tim dari berbagai multidisplin. Sebagai salah satu civil society, saya ingin pemerintah Indonesia dapat berbicara hal yang sama dengan tim kami waktu itu—memprioritaskan UU tentang obat-obatan agar aksesnya mudah. Jadi aku bantu advokasi, bertemu orang Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, dan menjadi perwakilan Indonesia untuk PBB. Akhirnya saat sidang, saya pergi sebagai delegasi untuk civil society Indonesia, yaitu organisasi-organisasi terlibat. Sidang tersebut isinya hanya pidato presiden, pidato para perdana menteri, dan kita hanya menyaksikan pidato-pidato orang tersebut. Namun, di sisi lain, ini adalah event besar—tempat orang dari seluruh dunia berkumpul menjadi satu. Terdapat banyak sekali side events—umumnya berupa workshop-workshop yang bermanfaat secara skill dan knowledge—yang diadakan oleh berbagai pihak. Sidangnya sendiri kan high level ya, saya cuma debu (sambil terkekeh). Namun, kerjanya itu sebenarnya terletak jauh sebelumnya (apabila bukan presiden—red) dan menyusun outcome document.
Apa pesan yang mau dr. Shela sampaikan untuk member CIMSA dan calon newcomers CIMSA?
Pesan dari saya adalah harus berani ambil risiko. Ambil risiko berarti apply ke CIMSA—mungkin akan bertemu orang-orang yang tidak disukai dan tidak cocok, membuang waktu tidur di national meeting. Tetapi, ambil risiko! Kalau takut, cobain dulu aja, ambil risiko. Kalau dipikir bisa/tidak, ya tidak akan bisa jika hanya dalam pikiran. Kita juga ambil risiko, bahkan di pasien. Orang sekarang tuh terlalu hati-hati, tetapi malah tidak mengerjakan apa-apa. Kalau misalnya dulu saya takut tidak bisa membagi waktu, saya tidak akan mendapatkan pengalaman yang bahkan tidak bisa aku bayangkan—seperti belajar menulis. Pokoknya, kalau mengerjakan sesuatu, jangan setengah-setengah. Hal tersebut hanya menambah pikiran.